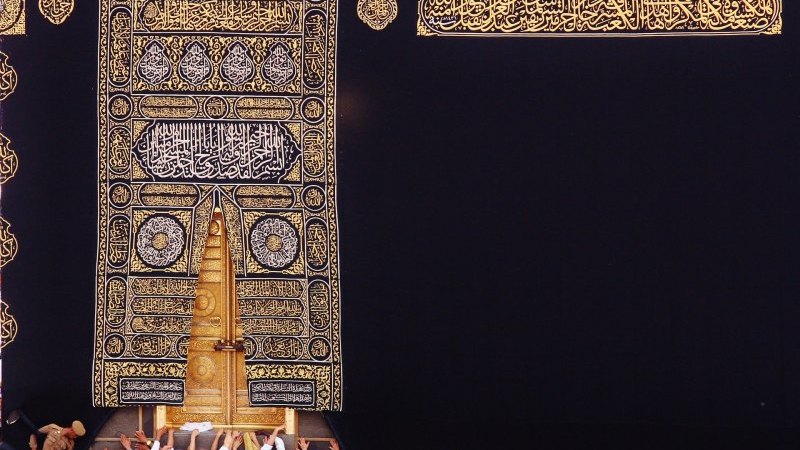
Kehidupan dunia mempunyai tatanan yang terus berkembang; sarat perubahan dan diwarnai dengan keterbukaan. Entah itu dalam skala kecil maupun besar. Tak terkecuali bidang informasi dan komunikasi yang selalu bergerak secara dinamis. Salah satunya pada ranah keilmuan. Secara mendalam, suatu ilmu tidak dapat berdiri sendiri. Karena permasalahan global yang terjadi terus berkembang dan semakin kompleks. Untuk menangani tantangan tersebut, dibutuhkan kreativitas dan inovasi beberapa kajian keilmuan untuk mengembangkan suatu kebaruan. Hal inilah yang dinamakan dengan interdisipliner ilmu.
Menurut Setya Yuwana Sudikan, interdisinpliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Bisa diartikan bahwa interdisipliner melibatkan dua atau tiga bidang ilmu bahkan bisa lebih untuk mengkaji suatu persoalan.
Interdisipliner menciptakan variasi sehingga muncul berbagai keunikan yang berbeda dengan hal-hal sebelumnya. Seperti halnya yang terjadi pada bidang sastra. Persoalan dalam bidang sastra selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Selalu memperbarui konsep cerita dan model kepenulisan. Sastra selalu mampu berkolaborasi dengan berbagai disiplin keilmuan. Sehingga dengan adanya fleksibilitas mampu menuangkan segala persoalan dan melalui sastra pun seseorang dapat mengetahui berbagai informasi yang tidak jemu hanya satu bidang saja. Begitu juga dengan sastra dan pesantren yang merupakan polemik yang notabene memiliki kelas yang berbeda di mata umum. Padahal jika ditelisik lebih lanjut, kedua bidang ini dapat bersimbiosis dengan baik yang mampu melengkapi di kedua lininya. Dalam perkembangannya, muncul aliran sastra yang dinamakan sebagai sastra pesantren. Sastra pesantren merupakan khazanah sastra Indonesia dan juga bagian yang tak terpisahkan dari sastra Indonesia. Abdurrahman Wahid dalam Sunyoto (2012) mendefinisikan sastra pesantren dalam dua defininisi; pertama karya-karya sastra yang mengeksplorasi kebiasaan-kebiasaan di pesantren dan kedua, adanya corak psikologi pesantren dengan struktur agama (warna religius) yang kuat.
Banyak karya sastra yang memunculkan identitas pesantren, baik yang diterbitkan oleh pesantren maupun luar pesantren. Pembentukan identitas karya sastra pesantren memiliki proses yang panjang yang menyejarah dan membentuk habitus tersendiri. Banyak buku yang dinarasikan berdasarkan kisah nyata perjuangan para ulama dan penceritaan kehidupan pondok yang jarang diketahui khalayak ramai. Bila dipelajari berdasarkan sejarah, karya sastra pesantren mengangkat tema-tema nilai esoterik keagamaan, dan cinta ilahiyah Toha Machsum (2013).
Menurut Hidayatullah dalam Toha Machsum (2013) konstruksi estetika sastra pesantren memiliki kekuatan roh yang transenden. Hal itu tidak terlepas dari ciri watak pesantren yaitu, ikhlas, sederhana (baca zuhud), terbuka, mandiri, dan cinta kepada ilmu pengetahuan Haedari (2006). Sehingga karya yang tercipta tetap fenomenal hingga sepanjang masa, sepeti film Sang Kiai yang disutradarai oleh Rako Prijanto. Film yang dirilis 30 Mei 2013 mengisahkan perjuangan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asyari dalam melawan penjajah Jepang bersama para santri. Selain itu, terdapat film Sang Pencerah yang ditulis dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film yang mengisahkan perjuangan KH. Ahmad Dahlan yang berjuang menyebarkan agama islam bersama santrinya. Hingga akhirnya beliau yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Masih banyak lagi film-film yang menceritakan tentang pesantren. Karya sastra pesantren tak hanya berupa film saja. Namun ada juga yang berbentuk prosa, syair, puisi, cerpen, dan novel.
Jika ditautkan dengan keberadaan penyair saat ini, ada beberapa sastrawan yang lahir menonjolkan dunia pesantren. Tokoh-tokoh tersebut mewarnai khazanah sastra pesantren, seperti Acep Zamzam Noor, D. Zawawi Imron, Zaenal Arifin Toha, Jamal D. Rahman, Abidah el-Khalqi, Kuswadi Syafi’i, Gus Mus dan lainnya. Bahkan menurut Gus Mus yang dilansir dari Republika.co.id menuturkan “Mbah Hamid (KH. Abdul Hamid Pasuruan) sejak di Termas sudah dikenal sebagai seorang sastrawan. Kyai Asad juga sastrawan. Tapi keduanya lebih menonjol kewaliannya.” Sastrawan pesantren lainnya adalah Hadratus-syekh KH. Hasyim Asyari. Menurutnya Mbah Hasyim suka membuat syair saat ada perbedaan pandangan dengan ulama lain agar tidak dipahami langsung oleh santrinya. “ini untuk menyembunyikan perbedaan pandangan di antara mereka, supaya santri tidak menganggap permusuhan. Saking hati-hatinya, mereka gunakan syair,” tutur Gus Mus. Kalau dilihat dari kaliber regional, ada pula ulama’ kharismatik dari Kota Malang yang bernama KH. Muhammad Yahya pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Malang, beliau juga menuliskan syair dengan nuansa tasawuf dalam kitab miftahul jannah.
Dengan demikian sastra dan pesantren merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Serta bukan hal yang perlu diperdebatkan untuk diklasifikasikan pada kelas-kelas tertentu atau bahkan sampai menyoroti bahwa sastra bukan sesuatu yang tidak baik untuk dipelajari.
Daftar Pustaka
Haedari, Amin. 2006. Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial. Jakarta: LeKDIS dan Media Surabaya.
Machsum, Toha. 2013. Identitas dalam Sastra Pesantren di Jawa Timur. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, No. 3, Hal 407-419, September Tahun 2013.
Sunyoto, Agus. 2012. Sastra Pesantren dalam Pergulatan, diakses 10 Maret 2022 dari http://media-sastrajatim.blogspot.com