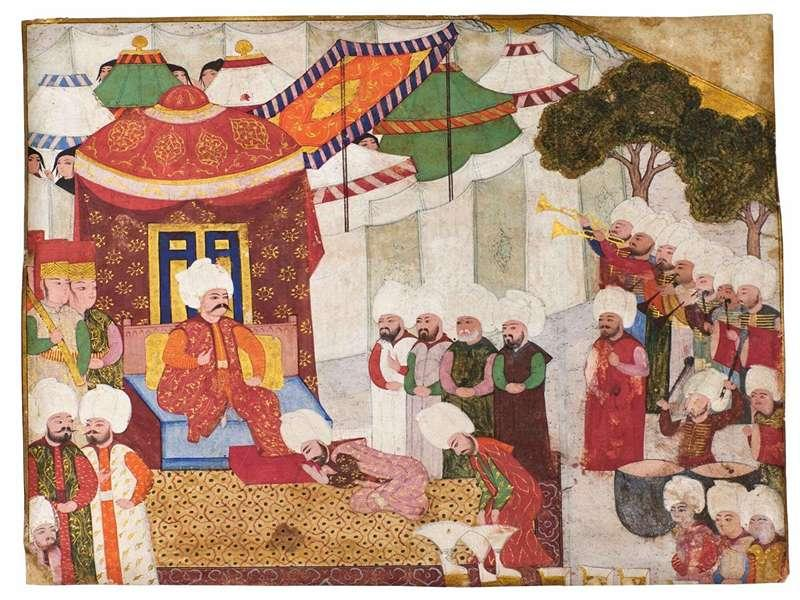
Ada suatu simpul yang menunjukkan identitas suatu golongan. Indonesia misalnya, tumbuh dengan ragam nilai, adat, bahasa, dan budaya. Lebih dari itu, kita dapat menganalogikan sesuatu yang kompleks bagaikan sebuah kain besar yang tenunannya terdiri atas benang-benang berbeda warna. Kain itu tampak indah, namun keindahannya hanya bertahan sejauh tiap benang rela saling menguatkan. Begitu satu benang longgar, sedikit demi sedikit, tenunan bisa robek.
Bayangkan pula sebuah perahu kayu yang terbuat dari papan-papan berbeda. Papan itu mungkin tidak serupa, ada yang lurus, ada yang melengkung. Tetapi ketika dipaku dengan tepat, ia menjadi tubuh perahu yang kokoh. Sekali saja ada papan yang berlubang, air akan masuk, dan seluruh perahu kehilangan daya apungnya. Atau seperti sebuah gamelan. Setiap bilah memiliki nada sendiri, tak ada yang sama. Namun, ketika dipukul bersama, terciptalah harmoni. Seandainya satu bilah tak mau dipukul dengan tepat, atau suaranya sumbang, seluruh alunan menjadi kacau.
Semua contoh itu mengajarkan hal yang sama, bahwa sesuatu yang besar dan berharga lahir dari kesediaan tiap unsur kecil untuk menunaikan fungsinya dengan sungguh-sungguh. Benang yang tampak remeh, papan yang hanya sepotong kayu, bilah gamelan yang sendirian tak berarti—semuanya ternyata menjadi penentu mutu dari keseluruhan. Laku menjaga mutu itulah yang sering menuntut kesabaran. Ada kalanya kita harus rela menahan diri dari godaan meremehkan peran kecil. Ada waktunya harus tekun merawat hal-hal sepele yang tak tampak mata. Di situlah tirakat itu bekerja dengan sebuah latihan panjang untuk setia pada peran, sekecil apa pun, agar keseluruhan tidak kehilangan bentuk dan nilai.
Kita dapat menyaksikan sirkus kehidupan itu. Kita kerap menemui hal-hal kecil yang sering dianggap sepele sehingga membuat batin masyarakat rapuh. Seseorang merasa wajar menunda janji, yang lain menganggap lumrah menyalahgunakan sedikit wewenang, lalu perlahan-lahan kelalaian itu menjadi budaya. Retakan kecil akhirnya menjelma jurang.
Di tengah jalan yang sunyi, seorang sufi pernah menolak sebutir kurma yang jatuh dari pohon. Alasannya sederhana, ia tidak tahu apakah kurma itu milik siapa, dan jangan-jangan bukan haknya. Sepele bagi orang lain, tetapi bagi dirinya, menelan sesuatu yang meragukan berarti merusak kesucian hati yang ia jaga. Dari keteguhan kecil itu lahir wibawa batin yang membuat kata-katanya dipercaya banyak orang. Di fragmen yang berbeda misalnya, seorang pemimpin besar menunda tidur malamnya hanya untuk memeriksa lampu minyak di ruang kerjanya. Bila ia menulis surat untuk kepentingan negara, lampu tetap menyala dengan minyak milik rakyat. Tetapi ketika urusannya berubah menjadi pribadi, ia memadamkannya dan menyalakan lampu lain dengan minyak yang ia beli sendiri. Perkara kecil, namun di situlah dasar keadilan berdiri.
Lain lagi dengan beberapa kisah seorang ulama’ kita yang setiap kali ditawari hadiah dari pejabat, beliau menolaknya. Bukan karena tidak butuh, melainkan karena tahu bahwa hadiah itu bisa membuat lidahnya enggan berkata benar suatu hari nanti. Keengganannya menerima hadiah menjadi manuver jiwa agar menjaga suara hatinya untuk tetap bebas.
Fragmen-fragmen itu mengingatkan bahwa mutu manusia justru diuji dalam hal-hal yang tampak kecil. Masyarakat sering menuntut pemimpin yang jujur, guru yang tulus, atau pedagang yang adil, tetapi lupa bahwa setiap orang juga dituntut menunaikan tirakat yang sama dalam lingkupnya sendiri. Jika benang kecil tidak dijaga, kain besar tak lagi utuh.
Kekuatan sebuah golongan, dari yang kecil (diri pribadi) hingga sebesar sebuah bangsa, terletak pada prinsip yang oleh Ibn Khaldun disebut ‘ashabiyyah, yakni ikatan batin yang membuat orang rela menahan diri demi kepentingan yang lebih luas. Namun, sejarah manapun menunjukkan bahwa ikatan itu rentan luntur ketika kesadaran bersama berubah menjadi kepentingan pribadi.
Di balik riuhnya tirakat integritas, Umar bin Khattab pernah mengingatkan dirinya sendiri dengan berjalan di malam hari memeriksa keadaan rakyat. Beliau mendapati seorang janda memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Umar segera memanggul gandum dari baitul mal dengan tangannya sendiri, menyalakan api, dan memasakkan makanan bagi keluarga itu. Laku sederhana yang seolah sunyi, namun dari sanalah martabat kepemimpinan bertumbuh dengan pengorbanan pribadi demi tegaknya keadilan bersama. Tirakat integritas semacam ini menyiratkan pesan yang tegas bahwa keutuhan masyarakat maupun individu tidak lahir dari kesetiaan manusia pada hal-hal kecil yang ia emban dengan penuh tanggung jawab.
Keadaan globalisasi saat ini menuntut penjagaan mutu karakter sebagai jawaban atas setiap laku moral manusia maupun identitas suatu kelompok. Pertanyaannya, apakah kesadaran itu benar-benar dihidupi, atau hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas yang memajang integritas sebatas slogan kolektif? Saatnya kita berkontemplasi dengan melihat sejauh mana kuasa atas diri sendiri yang dijaga, dan sejauh mana kita berani menakar kuasa orang lain dengan cermin yang sama.
Penulis adalah santri aktif di Pondok Pesantren Miftahul Huda sekaligus mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Malang