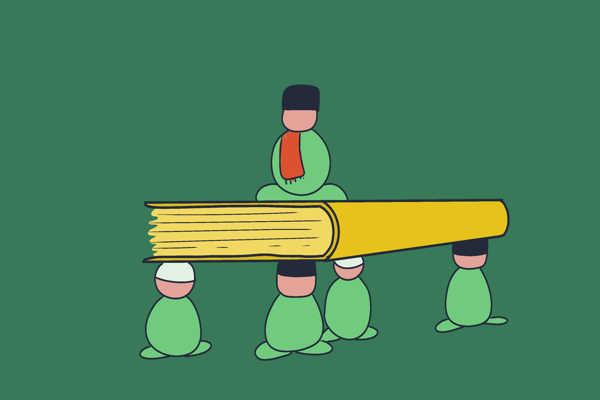
Pertemuan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas membuat pesantren sering diposisikan sebagai wilayah negosiasi ideologis. Di satu sisi, pesantren dianggap sebagai benteng moral bangsa, pusat pembentukan karakter religius, juga budaya etika sosial yang berakar kuat pada tradisi Islam Nusantara. Di sisi lain, muncul pandangan publik yang melihat pesantren sebagai lembaga yang mengekalkan struktur sosial feodal. Kiai diposisikan sebagai figur absolut, sementara santri dianggap tunduk secara hierarkis tanpa ruang kritis. Tuduhan semacam ini sering kali bersumber dari cara pandang modern yang menilai relasi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan rasional dan otonomi individu. Ketika standar itu diterapkan pada sistem tradisi pesantren, maka seluruh ekspresi penghormatan, ketaatan, dan pengabdian dipahami sebagai ketundukan feodal, bukan sebagai praktik moral yang berakar pada nilai-nilai adab dan spiritualitas.
Fenomena ini tampak, misalnya, dalam perbincangan di media sosial yang menyoroti relasi santri dan kiai dalam konteks kepatuhan. Beberapa pernyataan publik di platform X (Twitter) atau TikTok menilai bahwa pola komunikasi di pesantren merepresentasikan bentuk kultus individu terhadap kiai. Ada pula kritik dari kalangan modernis yang menafsir tradisi tabarrukan (mengharap keberkahan dari guru) sebagai simbol dominasi pengetahuan, bukan penghormatan terhadap sumber moral. Pandangan semacam ini merefleksikan suatu hal, yakni meminjam istilah Pierre Bourdieu, adanya benturan habitus antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional ketika struktur makna dan simbol sosial tidak lagi dibaca berdasarkan logika internalnya, tetapi selalu diukur dengan standar eksternal yang diidealkan oleh modernitas. Akibatnya, pesantren ditempatkan dalam wacana yang timpang, yakni sebagai entitas yang tertinggal atau bahkan ekosistem yang kolot karena tidak sepenuhnya mengikuti pola rasionalitas publik.
Apabila kita membaca melalui perspektif yang lebih reflektif, tuduhan feodalisme terhadap pesantren justru memperlihatkan keterbatasan cara berpikir publik dalam memahami rasionalitas moral yang hidup di dalam suatu sistem maupun tradisi. Max Weber misalnya, menjelaskan bahwa tindakan sosial tidak hanya digerakkan oleh rasionalitas instrumental, tetapi juga oleh rasionalitas nilai, yakni bentuk tindakan yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai etis atau spiritual tertentu. Maka, di dalam konteks pesantren kini, penghormatan terhadap kiai merupakan manifestasi dari rasionalitas nilai. Hal ini merupakan bentuk kesadaran moral yang terikat pada etika ilmu dan tanggung jawab rohaniah, bukan subordinasi sosial. Artinya, ketika publik membaca relasi kiai-santri sebagai hubungan feodal, mereka sesungguhnya sedang mengabaikan dimensi moralitas yang menjadi fondasi etika pesantren.
Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari dalam Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim, bahwa hubungan guru dan murid harus didasari pada adab al-nafs (pembersihan jiwa), bukan hubungan kekuasaan. Di sini, penghormatan kepada guru bukanlah kultus, tetapi bentuk kesadaran spiritual bahwa ilmu mengandung dimensi keberkahan. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahkan menegaskan bahwa pesantren adalah subkultur, yakni sebuah komunitas moral yang memiliki sistem nilai sendiri dan tidak dapat diukur sepenuhnya dengan logika rasionalitas modern. Maka, kritik yang memandang penghormatan sebagai feodalisme sering kali gagal memahami rationality of faith yang bekerja di ruang tradisi keagamaan.
Meski demikian, rasionalitas nilai yang menjadi dasar hubungan kiai dan santri tidak selalu berjalan dalam ranah yang murni etis. Di dalam realitas sosial misalnya, relasi ini kerap beririsan dengan logika kuasa simbolik yang bekerja halus melalui kultur adab. Di lapisan paling dalam lagi, tuduhan feodalisme terhadap pesantren memang muncul karena ketidaksadaran terhadap mekanisme kuasa simbolik tersebut. Tidak semua kiai menyalahgunakan posisinya, tetapi penghormatan yang semula dimaksudkan sebagai bentuk pengabdian spiritual dapat berubah menjadi wacana sakral yang menutup ruang kritik. Sebagai contoh, santri diberi pemahaman bahwa hidupnya berkah bila melayani guru tanpa pamrih, padahal layanan semacam itu bisa berfungsi sebagai sarana pendisiplinan batin agar santri terus menempatkan diri pada posisi subordinat.
Sebagian pihak memang tergesa menilai relasi kiai dan santri sebagai bentuk feodalisme hanya karena melihat pola penghormatan yang tampak hierarkis. Kiai seolah raja, dan santri tampak sebagai abdi yang tak punya otonomi. Padahal, narasi semacam itu belakangan banyak dikoreksi, baik oleh para ulama, kiai, maupun oleh pemikir islam yang menulis dari pengalaman langsung di lingkungan pesantren. Jika ditinjau dari sisi historis dan sosial, hubungan kiai–santri tidak berangkat dari logika kelas produksi seperti dalam struktur tuan tanah dan buruh atau kapitalisme industri, melainkan tumbuh dari tradisi keilmuan dan spiritualitas yang diikat oleh keyakinan serta adab. Apa yang tampak sebagai pengabdian, baik membantu pondok, bekerja di dapur, atau mengurus lahan lebih sering dijalankan sebagai laku kesalehan dan laku kerendahan hati, bukan sebagai bentuk kerja paksa. Karena itulah ketika menyebutnya sebagai eksploitasi jelas merupakan penyederhanaan yang gagal membaca konteks nilai dan niat di baliknya. Meski begitu, perlu diingat bahwa wacana adab yang mengatur hubungan tersebut dapat berubah arah, dari prinsip etika yang membimbing menjadi dogma yang menutup ruang berpikir. Ketika adab kehilangan dimensi reflektifnya, ia tidak lagi membangun kesadaran moral, melainkan mengikatnya dalam kepatuhan yang tidak memberi tempat bagi pertanyaan.
Apabila kita menelusuri berbagai tulisan dan kajian yang membahas pola patron–klien dalam konteks pesantren, tampak bahwa penghormatan kepada kiai kerap dilekati mitos kesakralan. Kiai dipandang sebagai “pewaris nabi” yang memiliki otoritas moral tak terbantahkan. Pandangan ini, meski berakar pada penghormatan religius, sering melahirkan konsekuensi sosial yang rumit. Begitu kritik dianggap sebagai bentuk kedurhakaan, adab kehilangan makna etiknya dan berubah menjadi perangkat penertiban kesadaran. Santri akhirnya belajar untuk diam bukan karena mereka sudah paham, melainkan karena takut menyalahi batas yang dianggap suci. Maka, seringkali dalam kondisi semacam itu, tradisi intelektual pesantren yang sejatinya berakar pada dialog dan pencarian makna justru terancam melemah oleh tekanan simbolik yang membungkus diri dalam nama kesantunan.
Apabila penghormatan kehilangan fungsi etisnya, ia berisiko menjadi dogma. Maka, konsep Antonio Gramsci tentang hegemoni moral menjadi relevan, bahwa kekuasaan kultural bertahan diterima sebagai kebenaran bersama atau kolektif, bukan karena paksaan. Ihwal Islam Nusantara, hegemoni semacam ini sering terpelihara melalui wacana kesantunan yang menolak kritik atas dasar adab. Padahal, sebagaimana disampaikan Nurcholish Madjid (Cak Nur), tradisi Islam sejatinya adalah tradisi berpikir terbuka, yang memuliakan akal dan mendorong perdebatan ilmiah sebagai bagian dari ibadah intelektual. Bila ruang berpikir tertutup, pesantren berpotensi kehilangan jati dirinya sebagai pusat ijtihad kultural.
Kekuasaan pesantren memang sering bekerja secara subtil melalui internalisasi wacana dan norma yang mengatur perilaku. Hal ini ditanamkan pada suatu keyakinan bahwa santri harus selalu menempatkan diri di bawah guru, bahwa melayani adalah bentuk tertinggi dari adab, dan bahwa keberkahan hanya dapat diperoleh melalui ketaatan tanpa syarat. Di dalam bentuk idealnya, pesantren dapat menjadi ruang dialektika, tempat santri belajar berpikir kritis tanpa kehilangan rasa hormat, serta menjadikan adab dan rasionalitas sebagai dua nilai yang saling menopang. Tetapi ketika konsep adab digunakan untuk membatasi pertanyaan dan menutup ruang perbedaan tafsir, maka yang lahir adalah kekerasan simbolik dengan dalih bahasa kesantunan.
Kritik terhadap relasi kuasa dalam pesantren seyogianya dipahami sebagai proses refleksi kultural yang bertujuan menyehatkan tradisi, bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadapnya. Di dalam konteks sosial-keagamaan, setiap sistem yang hidup dari relasi simbolik selalu berpotensi mengalami distorsi, termasuk ketika penghormatan berubah menjadi mekanisme kontrol (feodalism culture). Relasi kiai dan santri yang seharusnya berlandaskan etika keilmuan dan spiritualitas kadang beralih menjadi relasi hegemonik yang menuntut ketaatan total tanpa membuka ruang perbedaan tafsir. Karena itu, kritik perlu hadir sebagai bagian dari tradisi keilmuan pesantren itu sendiri, yakni tradisi yang historisnya tumbuh dari perdebatan, penafsiran, dan keberanian berpikir. Keberlanjutan pesantren justru bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara penghormatan dan rasionalitas, antara otoritas moral dan kebebasan intelektual. Tanpa keseimbangan itu, pesantren berisiko kehilangan daya pembaruan dan terjebak dalam kesalehan simbolik yang meniadakan daya kritis sebagai inti pendidikan. Wallahu A’lam
Penulis adalah santri aktif di Pondok Pesantren Miftahul Huda sekaligus mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Malang